Bahasa Ndakik-ndakik Disebut Sok Pintar dan Bikin Dosa? Lihat Dulu Konteksnya
Penulis: Achmad Fauzan Syaikhoni
Editor: Thiara
Cangkeman.net - Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang premis artikel ini—sebelum kalian membacanya sambil mengangguk-anggukkan kepala karena menyadari betapa pentingnya tulisan ini untuk dibaca dan dipahami. Heuheu….
Tulisan ini adalah buah pikiran dari keresahan saya setelah mendapat senggolan dari beberapa teman di dunia nyata maupun di dunia maya. Senggolannya cukup baik dan menarik untuk dijadikan pembahasan, terutama pada orang-orang yang hobi menulis dan membaca.
Senggolannya adalah permasalahan diksi akademis, atau kita akrab menyebutnya bahasa ndakik-ndakik. Iya, sebagian dari kalian mungkin sudah menangkap alur tulisan ini akan mengarah ke mana. Tetapi lebih jelasnya, senggolan teman saya ini mengomentari tulisan-tulisan yang diksi-diksinya itu rumit; ndakik-ndakik, yang katanya di satu sisi cuma menggambarkan sok pintar tapi sebenarnya dungu, dan di sisi yang lain menghasilkan dosa buat penulis karena membuat pembacanya kebingungan.
Udah, itu aja. Sekarang kita masuk pada pembahasannya.
Ada setidaknya dua vocal point yang ingin saya bahas di sini. Pertama-tama, senggolan atau kritik teman saya ini cukup subjektif menurut saya. Sebab, kalau penggunaan diksi akademis itu menggambarkan sok pintar tapi sebenarnya dungu, lalu mengapa diksi akademis ada di dunia kebahasaan dan kepenulisan? Dan, apakah orang-orang yang berkecimpung di dunia akademis itu berarti dungu dan punya banyak dosa?
Saya akan mengulitinya satu persatu.
Perihal pintar itu bukan diukur dari bagaimana seseorang berkomunikasi dengan menggunakan diksi-diksi sederhana atau ndakik-ndakik, tetapi diukur dari seberapa tajam logika dan koherensi penalarannya. Kalau diksi akademis itu predikat untuk kepintaran, maka semua orang bisa saja disebut pintar. Tinggal mau apa enggak mencomot diksi akademis meskipun tanpa tahu maksud dari diksi itu sendiri.
Memakai diksi akademis dikira sok pintar tapi sebenarnya dungu, itu parameter apa yang digunakan? Saya enggak akan menjawabnya, karena memang benar-benar enggak tahu bagaimana penalaran dari anggapan itu. Barangkali ada yang bisa menjawab atau bahkan meng-counter back, silakan. Saya cuma bisa memastikan, kalau teman saya ini mentalnya superior dan enggak mau merasa tersaingi dengan orang yang memakai diksi akademis, karena dia sendiri bisa jadi enggak paham dengan ‘mengapa’ harus memakai diksi akademis. Walhasil, framing itu yang disematkan.
Menyangkut dimensi teologis—atau yang katanya diksi akademis dapat mengakibatkan seorang penulis mendapat dosa—kira-kira siapa dia, sehingga punya otoritas untuk menentukan sesuatu itu berdosa? Atau, parameter apa yang dipakai sehingga diksi akademis dapat menimbulkan dosa?
Saya enggak mau menyebut dia cosplay jadi Tuhan, tetapi maksudnya adalah jangan terlalu serampangan ketika mengkritisi suatu persoalan. Tempatkan pernyataan kritik itu pada posisi yang tepat, mana yang akademis dan mana yang teologis. Jangan kemudian ujuk-ujuk disambungkan ke dimensi teologis agar terlihat kuat sehingga orang lain enggak bisa membantah. Kalau misalnya ada yang mau membantah, resikonya juga tinggi. Bisa-bisa, orang jadi berpindah agama karena argumennya mengenai hal teologis kalah sesudah dibantah. Kan, enggak lucu kalau kayak gitu!
Perihal si pembaca kebingungan ketika membaca tulisan yang ada diksi akademisnya, itu permasalahan mereka, bukan permasalahan penulis. Kalau seorang penulis itu harus mampu membuat si pembaca paham, lalu bagaimana seorang penulis mengetahui pemahaman pembacanya? Apakah harus survei dulu sebelum menulis? Kalau sudah tahu siapa yang akan membaca, ya, enak. Tapi kalau belum tahu siapa yang membaca, gimana?
Saya tahu, penulis yang baik itu karyanya dapat dipahami oleh banyak orang, terutama orang-orang yang enggak sempat terjun di dunia akademis. Tetapi sebuah tulisan itu menyangkut segmentasi pembaca. Enggak semua tulisan digeneralisir agar memakai diksi-diksi pada umumnya. Makna dalam sebuah diksi, dan konteks dari sebuah tulisan, itu saling berkorelasi dan ada proporsinya.
Misalnya ada kitab pegon, lalu dibeli sama orang yang belum bisa baca pegon; apakah si penulis kitab itu berdosa karena si pembaca kebingungan membaca kitab yang dibelinya? Atau, kalau ada buku filsafat, lalu dibeli sama orang yang sama sekali belum pernah belajar filsafat; apakah si penulis buku filsafat berdosa karena si pembaca kebingungan membaca buku filsafat? Sampai sini, saya harap akal kita sama-sama masih sehat.
Point yang kedua, orang yang memakai diksi ndakik-ndakik itu biasanya; ada yang ingin bergaya demi terlihat pintar; dan ada yang memang memakainya sebagai bentuk efisiensi penulisan kalimat dalam menyampaikan sebuah makna. Terkadang, diksi-diksi yang umum itu enggak bisa merepresentasikan makna tertentu, terutama makna yang perlu pemahaman tinggi. Kalaupun bisa, kalimatnya panjang.
Misalnya satu contoh kalimat, “kritisisme sebagai resolusi yang relevan atas banyaknya kasus hoax”. Dua diksi “kristisisme” dan “resolusi” ini enggak bisa diwakilkan dengan diksi-diksi pada umumnya. Karena komposisi maknanya cukup kompleks. Bisa saja kalau dipaksakan memakai diksi umum, tetapi jadinya akan seperti ini, “aliran filsafat yang mengupayakan kemampuan rasio untuk menyelidiki pengetahuan dan batas-batasnya itu sebagai putusan baru yang berkaitan atas banyaknya kasus hoax”. Jadi panjang dan malah nambah njelimet, kan?
Sekali lagi, bukan berarti mengharamkan pemakaian diksi-diksi sederhana, tetapi antara diksi umum dan akademis itu ada proporsinya; ada tempatnya. Entah tulisan yang bertajuk sastra, filsafat, teologi, psikologi, sosiologi; itu tergantung konteks orientasinya akan dikemanakan, untuk apa, dan untuk siapa. Kalau konteksnya di ruang akademis dalam rangka simposium—ya, diksi ndakik-ndakik justru harus ada—supaya makna dan situasi akademisnya tetap hidup. Tetapi kalau untuk kalangan umum; bertujuan edukasi, misalnya, ya sudah seharusnya menyederhanakan diksi agar mudah dipahami.
Jadi, jangan selalu menganggap keberadaan diksi ndakik-ndakik itu buruk. Apalagi kalau menganggapnya hanya karena belum paham dan belum mampu menggunakannya. Kalau memang bingung ketika mendengar/membaca diksi semacam itu, apa salahnya bertanya dan belajar mencari maknanya?

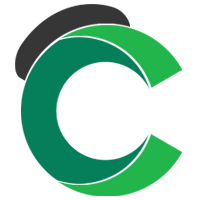


Posting Komentar